Cerpen
(Cerpen ini sudah dihantar di DBP Caw Sabah untuk tujuan penerbitan)
Seikhlas Hati
| Kata-kata dari sms minggu lalu “Rin, cepat urskan tanah rumah kamu! Waris-waris Haji Hamid sudah sedia memasukkan nama kita dengan membayar saguhati seikhlas hati,” Kak Sal. |
Berulangkali aku membaca sistem pesanan ringkas dari abangku itu. Dia panjangkan dari sistem pesanan ringkas Kak Salamiah. Aku tidak mahu memberikan banyak komen. Lebih berdiam diri dan bertemu dan aku tidak sabar hendak bertemu dengan penerima berita yang sahih.
Hujung minggu itu aku balik ke kampung bagi membincangkan tanah waris yang sedang kami duduki itu. Kami hanya duduk di atas tanah itu atas nama belas kasihan dan sebuah wasiat tulisan tangan. Aku pula sengaja ingin balik ke kampung bagi menyuarakan kerinduanku kepada kampung halamanku sendiri. Namun, aku tetap berasa bimbang juga terhadap ketiadaan surat kuasa untuk kami menduduki tanah itu. Silap hari bulan waris Haji Hamid itu membawa traktor untuk menyahtiadakan rumah yang dibina ayah sejak tiga puluh tahun ini. Uh, minta dijauhkan bala!
“Salah seorang dari kita akan masuk nama bang? Abanglah yang sesuai masuk nama ke dalam geran ‘tu! Sudah bertahun kita tunggu benda ‘tu!” jawabku ketika kami berbual-bual di ruang tamu. Perasaan gembira meresap di hati. Abang sulungku itu mengangguk-angguk sambil sambil senyuman merekah di wajah bujurnya.
“Sudah tentu! Nama abanglah yang akan dimasukkan ke dalam geran besar ‘tu!” katanya mendabik bangga. Aku tersengih malah sedikit terkilan. Nama arwah ayah tidak sempat dimasukkan ke dalam geran besar itu. Entah apakah dosa kami semua sehingga pewaris tanah sebenar itu bersungguh-sungguh tidak mahu memasukkan nama ayah ke dalam geran. Ayah mengusung surat wasiat ke sana sini. Masih kemas dalam tinta kenanganku wajah sayu ayah itu. Masih kemas dalam lipatan ingatan semuanya. Ketika itu aku yang masih kecil memerhatikan ayah penuh kesedihan, kalaulah aku ada sebuah kuasa!
“Berapa mereka minta?” soalku ingin tahu. Abang sulungku itu tersenyum.
“Tak baca sms?” soalnya seperti menghina. Pandangan matanya bertambah menyakitkan hati. Soalanku dibalas dengan soalan. Memang abangku tidak faham soalan. Aku mengerutkan kening.
“Baca, saya baca! Dah khatam 44 kali! Tapi, takkan dia orang minta dengan seikhlas hati saja! Tak percaya saya! Sungguh saya tak percaya!” jawabku lantang dan berulang-ulang.
Mustahil keluarga tuan tanah yang diketuai oleh waris-waris terdekat Haji Hamid itu akan bermurah hati kepada kami anak ayah. Ayah yang sepanjang hayatnya, mereka aniaya dan hari ini mereka memberikan penghormatan kepada kami tanpa meminta wang walau sesen pun? Memang tidak masuk akal, sudut hatiku yang paling dalam menyangkal kata-kata abangku itu.
“Ha, sudah tahu? Apa lagi mau tanya!” sinis suara abang. Abangku seperti sudah terlupa akan kemurungan yang melanda ayah kerana dolak-dalik dan politik kotor permainan waris-waris terdekat Haji Hamid. Sungguh aku hairan dengan keadaan abangku. Khuatir pun ada. Khuatir kalau-kalau dia dijual siang hari. Sungguh tidak berfikir, sarat akalku mengusik.
“Oh ya? Bagus betul berita ‘tu? Siapa sampaikan berita yang sangat bagus ‘tu?” sengaja kutekan suara apabila menyebut perkataan ‘bagus’. Aku keliru kenapa abangku jadi begitu, agak kebingungan dan kurang memikirkan sesuatu yang serius secara waras. Mungkinkah sejak ketiadaan ayah dia begitu? Pasti bukan sebab ayah! Jawab hatiku sendiri.
“Kau tak faham lagi? Berita tu disampaikan oleh Kak Salamiah! Dia pun gembira kalau hanya membayar mengikut keihklasan hati kita sahaja!” jawab abang sulungku itu. Aku geleng kepala. Aku beristighfar dalam hati. Aku memang masih tidak boleh terima akan kata-kata itu. Kata orang cakap abangku tak boleh pakai!
“Tanah mereka pun akan dibayar seikhlas hati?” soalku masih ragu. Wajah Kakak Salamiah yang cengkung menari-nari di mataku.
“Samalah! Dia lah yang beritahu abang minggu lalu!” jawab abang sulungku. Aku menggeleng, masih mengesahkan bahawa berita yang kudengar itu palsu dan tidak masuk akal.
“Berasaskah itu? Padahal selama lebih 40 tahun ini, itulah perniagaan mereka, menjual tanah kepada orang luar dengan harga tak berbaloi, abang tak perasan?” soalku cuba menyedarkan abangku yang hampir terlelap oleh tekanan hidup itu. Dia memandangku tajam. Mungkin banyak stok jualannya yang belum terusik menyebabkan abang bingung begitu.
“Kau ni suka mengungkit sesuatu yang sudah lama! Mungkin mereka sudah buka buku baru!” jawabnya. Aku bertambah kesima. Malah lebih hilang percaya akan kata-kata abang. Aku tidak mahu menekan lebih-lebih akal abangku itu tetapi aku harus menyedarkan dia sebelum dia terlena di dunia yang serbanya gagah dan bergerak pantas ini. Memang aku sesekali tidak percaya kalau waris Haji Hamid mengubah fikiran mereka setangkas ini pula, memberi kami hak tanah secara seikhlas hati sahaja! Memang tidak boleh dipakai pada zaman serba muktimedia ini!
“Abang cuba fikir baik-baik, setelah lebih 40 tahun ayah kita tak dapat masuk nama dalam geran tanah di kampung kita ‘tu, lepas tu, setelah ayah kita meninggal dunia, tanah masih merah, air mata belum berhenti dan ingatan belum habis, mereka sudah minta kita lunaskan RM50 ribu, boleh-boleh hari ini mereka minta hanya seikhlas hati kita? Boleh masuk akal bang?” soalku. Pandangan kami bertembung seketika. Masing-masing meluahkan perasaan yang sungguh bertentangan.
“Sudah tak pakai lah tu! Mereka hanya mahu seikhlas hati kita saja! Kau tak baca sms Kak Salamiah?” jawab abang dengan tenang dan seolah-olah hujahnya itu adalah kebenaran. Aku betul-betul tidak percaya. Malah, bukan senang-senang aku akan percaya akan hal itu. Sampai masuk kuburpun aku belum tentu akan percaya akan kenyataan itu kecuali aku sudah hilang pendengaran, mungkin aku terpaksa percaya.
“Betul kah ‘tu bang? Bukankah selama ini mereka memang tunggu sangat bayaran duit dari hasil titik peluh kita? Apatah lagi kita masing-masing sudah berjaya dalam pelajaran dan mempunyai pekerjaan baik-baik! Takkan sekarang senang-senang mereka bermurah hati kepada kita adik-beradik? Boleh pakaikah cakap abang ‘tu?” soalku cuba membuka akal abangku yang seakan tertutup itu.
Dia tetap mengangguk juga. Aku geram dengan sikapnya itu. Seorang lelaki yang pernah bapa sandarkan harapan agar menjadi tunggak untuk menegakkan kewibawaan, tetapi dia pula bersikap agak kurang normal. Memang di luar kebiasaan.
“Memang mereka sudah bincang dan tak minta apa-apa! Mereka bagi ihsan kepada kita! Kenapa kau tak bersyukur?” bantah abang pula. Aku tersengih. Entah siapa yang merasuk kepala abang sehingga menjadi sasau begini. Aku sungguh berasa kesal dan hampir menangis di saat itu juga.
“Begitu? Dulu, bukan main lagi beriya-iya! Sekarang, senang-senang cakap bagi seikhlas hati? Adakah ini kebenaran atau gurauan? Atau abang salah baca sms?” soalku pula. Kupandang mata kuyu itu cuba menumpangkan keupayaan dan keyakinan di hatinya.
“Kau ni macam tak percaya pula! Dia orang minta seikhlas hati, kau tak percaya? Atau kamu mahu bayar RM50 ribu tu?” aku ketawa sinis. Soalan itu sungguh sinis sekali. Aku sangka abangku itu sudah lupa mengenai harga tanah yang dipinta dulu, rupanya dia masih ingat. Syukurlah kalau dia masih ingat dan waras.
“Kalau seikhlas hati dari kita ialah RM1 setiap seorang, semuanya menjadi RM8, apakah mereka akan terima wang seikhlas hati kita ‘tu?” soalku memberikan pandangan agar dia berfikir lebih jauh lagi. Bulat matanya memandangku.
Sebenarnya aku mahu menangis saat ini juga. Istilah seikhlas hati hampir lupus dalam kamus masyarakat kampung akhir zaman ini. Apatah lagi dengan perjuangan kami memasukkan nama salah seorang adik-beradik ke dalam geran tanah Haji Hamid, istilah seikhlas hati menjadi sangat tipis. Kenapa abangku yang sulung itu semudah itu percaya kepada kenyataan yang datang dari khabar angin itu? Kenapa abangku itu seolah-olah hilang pertimbangan?
“His kau ‘ni sudah melampau dik! Kalau nak seikhlas hati ‘tu, agak-agak lah! Janganlah sampai nak bagi satu ringgit! Mereka sudah lah bermurah hati bagi nama kita masuk nama dalam geran tanah, kau pula bagi seringgit! Apalah jenis manusia lah kau ‘ni?” katanya pula. Aku ketawa. Ketawa sungguh-sungguh. Bicara abangku itu memang sungguh lucu.
“Itulah seikhlas hati bang!” aku ketawa lagi. Dia sudah menjeling aku. Mungkin semakin geram dengan kata-kataku.
“Jangan lah macam tu pula! Sekurang-kurangnya kita bagi sesuatu yang lebih besar,” katanya memberikan cadangan. Aku mengerutkan kening. Aku tidak menerima cadangan itu. Malah, aku tidak percaya dengan perkataan seikhlas hati itu. Sungguh tidak aku akan percaya walau seribu tahun lagi.
“Itulah harga seikhlas hati bang, kalau tidak tak perlu bagi apa-apa saguhati pun kepada tuan tanah, kita berdoa sahaja agar mereka sekeluarga sampai ke anak cicit mereka akan selamat dunia akhirat, setuju bang?” aku memberikan pandangan lagi. Terbuntang matanya.
“Kau betul-betul tak ada harga diri, adakah patut nak doa saja! Patutnya kita semua bagilah wang saguhati agar mereka lebih gembira mengembalikan nama kita di geran mereka,” aku ketawa lagi. Abangku ini memang sudah lupa asal-usul kejadiannya. Aku menjadi hilang kata. Perlukah aku angkat beg sahaja dan pulang ke rumahku sendiri? Sementelah keretaku menunggu di garaj rumah ayah ini? Aku berkira-kira angkat kaki sahaja. Buang masa aku berbicara dengan manusia bingung di depanku itu.
“Pergi tanya semula dengan tuan tanah bang! Mari kita tanya sekarang! Rumahnya bukan jauh, hanya selang dua buah rumah sahaja dari kita. Hmm, saya tak percaya kalau mereka murni hati begitu! Lagipun abang hanya dengar cakap orang! Cuba tanya sendiri tuan tanah dulu!” gesaku lagi. Bulat matanya.
“Kau ni tak bersyukurlah dik! Abang sudah sampaikan apa yang benar dan ditunggu-tunggu tetapi kau tak mahu percaya!” aku pandang dia. Ak geleng kepalaku. Kesal bertabur-tabur di sepanjang pandangan mataku ke arahnya.
“Siapa mahu percaya? Mereka tu lintah darat tau! Mereka takkan bagi kita dengan barang dagangan mereka dengan sewenang-wenangnya. Apatah lagi setelah hampir 50 tahun! 50 tahun bang! Abang ingat waris-waris Haji Hamid seperti Amin, Fadil, Awang, Roslee itu akan bagi kita tanah secara percuma? Tanah dekat jalan dan jenis geran CL lagi? Boleh percaya mereka akan bermurah hati memberi kita yang miskin ini bang? Cuba abang fikir,” kataku semakin lantang. Aku mahu abangku itu buka mata dan menurut perbincangan yang paling afdal. Bertemu dengan waris Haji Hamid yang merupakan pemegang geran tanah tersebut.
“Jangan menuduh yang bukan-bukan dik! Setelah mereka bermurah hati meminta kita sediakan seihlas hati saja, sepatutnya kita berterima kasih,” jawabnya pula. Aku geleng kepala. Rasa berpinar kepalaku mendengar bicaranya. Kata-kataku sentiasa patah oleh hujah autanya itu. Hancur hatiku dengan sikap abangku yang senang-senang diperbodohkan begitu. Mahu sahaja aku ketuk kepalanya.
“Abang tahu tak, dua minggu lalu anaknya datang dan minta RM50 ribu secara senyap-senyap kat abang Ghani. Hari ini tiba-tiba mereka minta seikhlas hati? Bolehkah terima dengan logik akal? Atau, mereka menang loteri RM100,000.00?” aku ketawa kemudiannya. Bagaikan lelucon. Bulat mata abang memandangku. Aku tidak peduli.
Aku hanya memberikan kenyataan yang sebenar bukan khabar angin. Malah, aku rasa, abangku ini jarang sekali berfikir. Dia hanya mengutip fakta daripada orang lain. Bolehkah aku berkongsi kenyataan dengan dia kalau kenyataan itu palsu dan tidak boleh dicerna akal?
“Ketawalah kau! Ketawa lagi! Nanti kalau aku sudah masuk nama, kau jangan dengki pula!” katanya. Aku kerut kening. Benarkah abangku ini hilang waras? Berulang kali soalan itu menerobos akalku. Mahu sahaja aku gali semula kubur ayah dan memulangkan kebenaran itu.
“Dengan seihklas hati? Sungguh lucu kan!” soalku sinis. Dia memandang jauh ke luar rumah kami. Buah gajus sedang berbuah dengan lebatnya. Dulu sewaktu aku masih kanak-kanak, waktu begini aku masih memungut biji buah gajus itu untuk dibakar di periuk hitam emak. Paling malah lagi kenangan itu, aku memungut buah gajus itu dengan waris paling dekat tanah yang kami duduki ini, Siti. Entah di manakah Siti sekarang, sukar kupadam kenangan itu. Tetapi apabila tanah sekangkang kera ini tidak dipedulikan nanti, entah ke mana kami adik-beradik akan berkumpul terutama pada waktu perayaan atau cuti.
“Ah, sudahlah kau! Bercakap dengan kau ni memang tak boleh pakai!” his, aku pula yang dicakapnya tak boleh pakai. Memang tidak boleh jadi! Dia sudah berdiri sambil menarik seluar putih ke pinggangnya. Mungkin dia terasa sungguh geram dengan kata-kataku.
“Siapa yang tak boleh pakai? Yang seikhlas hati atau abang atau saya?” soalku semula. Aku tetap memaksa dia berfikir semula. Aku mahu dia sedar dan buka mata besar-besar. Bukannya diperbodohkan sepanjang hayatnya.
“Sudahlah kau! Baik aku cakap dengan monyet hidung panjang, boleh lagi faham! Kau ‘ni memang susah!” jawabnya. Aku bertambah sebak tetapi dalam masa yang sama aku tetap geli hati dengan pendirian abangku itu.
“Siapa yang menyusahkan macam monyet panjang hidung? Aku, abang atau seikhlas hati?” aku soal dia semula seolah mencabar abangku sendiri.
“Sudahlah kau, baik aku jalan dulu!” katanya. Cepat-cepat abang capai kasut dan kunci kereta. Waktu cuti yang sepatutnya kugunakan untuk bercuti seolah-olah telah hilang oleh seikhlas hati.
“Abang, abang ingat zaman multimedia dan zaman material ni, ada orang yang akan melepaskan produknya ke tangan orang lain dengan percuma atau seikhlas hati?” tukasku sebelum dia menuruni anak tangga rumah arwah ayah yang namanya belum tercatat di atas geran tanah.
“Kau memang tidak boleh dibawa berbincang!” katanya lantang suara. Aku geleng kepala lagi. Aku rasa kepalaku, aku memang pening dengan gelagat abangku sendiri. Sudah dibekalkan pelajaran tinggi tetapi dia masih berperangai seperti budak-budak. Manusia apakah itu? Tentu bapa berasa sedih dengan sikap abang. Aku yang masih hidup ini lebih-lebih lagi sedihnya.
“Abang silap! Abang silap! Abang yang tak mahu dengar cakap adik-adik dan anggap kami macam sampah! Abang anggap hanya abang yang betul! Sebenarnya abang pun kena dengar cakap adik-adik!” jeritku agak kuat. Aku tidak peduli kalau emak yang tiba-tiba muncul dari biliknya akan menjeling aku.
“Sudah! Sudah! Aku tak mahu dengar! Kau yang tak mahu dengar cakap aku!” katanya tergesa-gesa dan geram. Aku ketawa.
“Dengar dulu bang! Jangan jalan dulu! Kalau benar dia minta RM50,000.00, abang bayar ya dan abang masukkan nama abang seorang. Tanah ni abang punya! Dan, jangan bawa kami bincang!” dia pusing semula ke arahku yang sedang berdiri di bibir tangga. Aku senyum sinis. Kemudian dia berpusing memandang kereta D’maxnya sambil menekan punat kekuncinya. Aku akan tunggu beberapa hari lagi. Aku akan tunggu perkembangan yang selanjutnya. Masa akan menjawab siapa yang menang, bisik hatiku.
Dalam hati aku lebih terkilan dengan tindakan abang sulungku dan lebih terkilan kalau tidak ada sesiapa yang mengusahakan membayar harga tanah di pinggir jalan yang kami duduki sejak lebih empat puluh tahun yang lalu!
***
Deringan telefonku mengejutkan aku dari barisan rasa terkilan ketika berbual bersama abangku.
“Assalamualaikum, ya kenapa?” adikku yang kebetulan tinggal di kampung. Pasti ada perkhabaran gembira, dugaku atau khabar tak gembira.
“Keluarga arwah Haji Hamid panggil wakil kita berbincang. Bayaran minta disediakan,” aku ketawa. Aku memang sudah jangka. Tidak ada rasa terkilan atau terkejut.
“Jadi? Bukan seikhlas hati?” soalku sinis.
“Huh! Siapa yang salah dengar tu? Kakak Salamiah mungkin salah anggap!” kata adikku. Dia turut ketawa.
“Jadi, bukan seikhlas hati?” soalku lagi menekan perkataan seikhlas hati itu.
“Mana ada! Tetap mahu RM50,000.00. Kalau lambat buat bayaran, nilai itu akan dinaikkan! Harga hartanah semakin naik kak!” jawab adikku.
“Memanglah! Sudah beritahu abang?” soalku.
“Sudah!”
“Apa dia cakap?” aku ingin tahu apa yang dia mahu cakap.
“Entahlah, dia macam pasrah sahaja tu,” jawab adikku.
“Bayaran dia nak keluarkan?” soalku.
“Entah, dia tak banyak cakap!” jawab adik lagi.
“Tak apa, kita sudah mendapat kepastian!” jawabku tersenyum riang.
“Mana ada keluarga Haji Hamid tu nak bagi kita percuma kak! Mustahillah!” tokok adikku. Aku menahan rasa; marah, benci, gelisah, pedih dan risau kembali berbaris di dadaku ini.
“Itulah hakikatnya. Tidak ada benda percuma lagi dalam dunia ini, apatah lagi seikhlas hati! Beras pun dah naik! Masuk tandas pun RM0.50. Huh, kalau tak perasan lagi benda kecik macam tu, kak tak tahu lah!” huraiku.
“Susah kak, kita sendiri yang tak mahu fikir dan bersatu hati,” tambah adik lagi.
“Kita yang salah faham dan rugi masa berpuluh-puluh tahun tapi abang kita yang satu ‘tu tak mahu percaya! Sekarang siapa yang rugi? Kita juga kan?”
“Kita pakat bayar lah kak, kalau tak tanah rumah ni akan jatuh ke tangan orang lain! Jiran-jiran kita ni ada yang sanggup mengganti!” sungguh di luar kepercayaanku. Hatiku bagaikan ditusuk sembilu. Alangkah kejam! Sedih bersatu dengan kehilangan. Kehilangan sebuah tempat di mana berkumpulnya kenangan. Kenangan yang tergadai oleh sekangkang tanah!
“Kak, tidur?” aku tersedar.
“Ya, kita akan bincang benda, jangan biarkan tanah kita jadi santapan si penyangak yang tak perikemanusiaan. Kalau tidak, habis tergadai semua kenangan kita!” adikku ketawa di hujung corong telefon. Aku tersengih.
“Kita jumpa hujung minggu, beritahu abang dan adik-beradik yang lain! Kita pakat!” kataku muktamad.
KK/KP/S’NA-20112012
NORAINI BT OSMAN
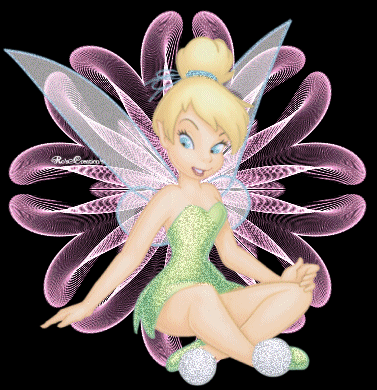
No comments:
Post a Comment